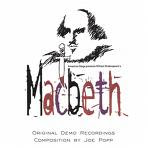
Politik, seperti halnya tragedi, tak akan punya arti tanpa kesangsian. Mungkin itulah sebabnya Macbeth, tragedi Shakespeare, tak mudah dilupakan, juga oleh seorang presiden.
Pada suatu malam sastra di Gedung Putih, Presiden Clinton bercerita bahwa perkenalan pertamanya dengan puisi berlangsung di SMP, ketika gurunya memintanya menghafal baris-baris solilokui dalam Macbeth. Lalu ditambahkannya, setengah melucu: untuk memasuki kehidupan politik, membaca Macbeth bukanlah awal yang baik.
Ketika acara selesai dan hadirin bergiliran menjabat tangannya, seseorang bertanya masih ingatkah presiden itu baris-baris Macbeth itu. Di saat itu Clinton pun membacakannya dengan bagus:
… here upon this bank and shoal of time,
We’d jump the life to come. But in these cases
We still have judgement here, that we but teach
Bloody instructions which, being taught, return
To plague th’inventor.
Kalimat itu diucapkan Macbeth, ketika tokoh lakon ini sendirian, merenung dalam kebimbangan. Panglima perang itu berniat membunuh rajanya, Duncan, meskipun ia tahu baginda menyayanginya dan mempercayainya: Duncan telah menghadiahinya wilayah kekuasaan yang lebih luas dan bersedia datang menginap di kastilnya. Tapi Macbeth berniat membunuhnya, karena ada ramalan tiga nenek sihir bahwa ia akan jadi raja.
Dan tak kalah penting, karena Lady Macbeth, istrinya yang perkasa, mendesaknya, meyakinkannya.
Malam itu Macbeth pun membunuh raja, ketika tamu agung itu tengah tidur. Untuk menghapus jejak, ia tuduh dan ia bunuh para penjaga. Darah yang mengalir tak berhenti di sana….
Tapi sesaat itu, ketika ia sangsi, ketika ia merasa berada ”di tebing dan laut waktu”, Macbeth bukan seorang yang keji. Ia merasa ada yang tak patut bila ia jalankan niatnya: ia mengkhianati rajanya dan membantai seorang ”lemah lembut” (meek), yang ”kebajikannya akan mengimbau bagaikan malaikat”, hingga akan jatuh kutuk ketika ia dipaksa meninggalkan dunia.
Memang tak jelas benar apa yang membuat Macbeth bimbang: seperangkat nilai-nilai, sebuah tatanan moral, atau hanya ketakutan pembalasan. Kita dengar baris yang dibacakan Clinton: siapa yang membawa ajaran berdarah, kata Macbeth, akan mendapatkan yang sama, yang berbalik, merongrong ia yang memulanya.
Mungkin dalam ambivalensi itu antara bisikan moral dan dag-dig-dug ketakutan dengan mudah bujukan Lady Macbeth menjeratnya. Menjerat: sebab Duncan mati, Macbeth jadi raja, tapi sejak itu yang ada hanya pembunuhan demi pembunuhan. Macbeth tragis karena kita sebenarnya bisa melihat apa yang baik dalam dirinya tapi nujum dan nasib tak ditolaknya. Ia jadi keji.
Bukan karena nujum dan nasib itu sebegitu sakti. Macbeth, dengan kemauannya sendiri, memilih nujum dan nasib dan bukan yang lain. Dia juga yang bolak-balik datang meminta nujum dari tiga nenek sihir itu, bahkan mencoba mengubah ramalan yang tak disukainya.
Macbeth tragis, sebab kita menyaksikan bagaimana kekuasaan meringkus semuanya. Termasuk meringkus saat-saat sangsi di depan ”tebing dan laut waktu” sebelum seseorang meloncat ke masa depan saat-saat ketika bisikan yang lain masih bisa terdengar.
Saya tak kunjung takjub apa sebabnya hasrat ke kekuasaan mampu meringkus semua itu. Apa yang istimewa dalam kekuasaan? Mengapa segala cara dikorbankan untuk mendapatkannya? Akhirnya ada yang lebih destruktif ketimbang pembunuhan—yakni sejenis nihilisme, yang menegaskan bahwa kita tak perlu sangsi karena kita tak perlu nilai-nilai. Tak ada dorongan yang gigih untuk mempertahankan apa yang baik. Seperti kita lihat di Indonesia kini, uang, jual-beli pengaruh, lewat lobi dan media, itulah yang akhirnya menentukan apa dan siapa yang salah dan apa dan siapa yang tidak. Selebihnya: nihil.
Apa lagi gerangan yang dikenang seorang presiden seperti Clinton setelah membaca Macbeth? Clinton sendiri mungkin tak perlu merenungkan jauh; ia tak perlu bergulat dengan dilema yang dahsyat. Ia seorang presiden yang dapat naik dan turun takhta tanpa melalui pembunuhan.
Maka menarik untuk menyimak apa yang dikatakan Clinton kepada Stephen Greenblatt yang kemudian menuliskan kesannya dari malam sastra di Gedung Putih itu dalam The New York Review of Books, 12 April 2007. Karya Shakespeare itu, kata Clinton, adalah kisah tentang seseorang dengan ambisi yang amat besar yang ”obyeknya secara ethis tak memadai”.
Ada yang baru di sini: bukan si Macbeth yang ”secara ethis tak memadai”, melainkan sasarannya: kekuasaan. Mungkin yang dimaksud Clinton bukan kekuasaan pada umumnya (rasanya ia tak hendak berpikir demikian tentang kekuasaan seorang Presiden Amerika), melainkan kekuasaan yang direbut Macbeth. Dalam lakon ini, kekuasaan bukan saja tampak tak sah, tapi juga tak ada tujuannya. Atau lebih tepat: kekuasaan dipertahankan demi menyembunyikan sifatnya yang tak sah. Macbeth adalah cerita tentang nihilisme dalam bentuknya yang mengerikan dan menyedihkan, karena seorang baik telah mengikuti nujum dan nasib, dan tenggelam dalam kekejian—seraya menyimpulkan bahwa hidup hanyalah ”kisah yang dibawakan seorang dungu, penuh amarah dan suara seru, yang tak punya arti apa-apa”.
Suaranya sebenarnya murung. Di saat itu Macbeth justru menunjukkan: nihilisme tak bisa mutlak. Dengan getir ia sendiri merasakan ada yang hilang di dunia ketika hanya kekuasaan yang tak menyebabkannya hidup tenteram telah jadi satu-satunya perkara yang dipertaruhkan.
Syahdan, di kamarnya yang gelap, setelah pembunuhan terjadi, Lady Macbeth tiba-tiba merasa melihat ada darah di tangannya. Berjam-jam ia coba basuh, tapi tak terhapus juga. Jejak kejahatan itu tetap bau. Dan akhirnya ia tahu: ”seluruh parfum dari Arabia tak akan dapat mengharumkan tangan kecil ini”.
~Majalah Tempo Edisi Senin, 21 Desember 2009~
http://caping.wordpress.com/page/2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar